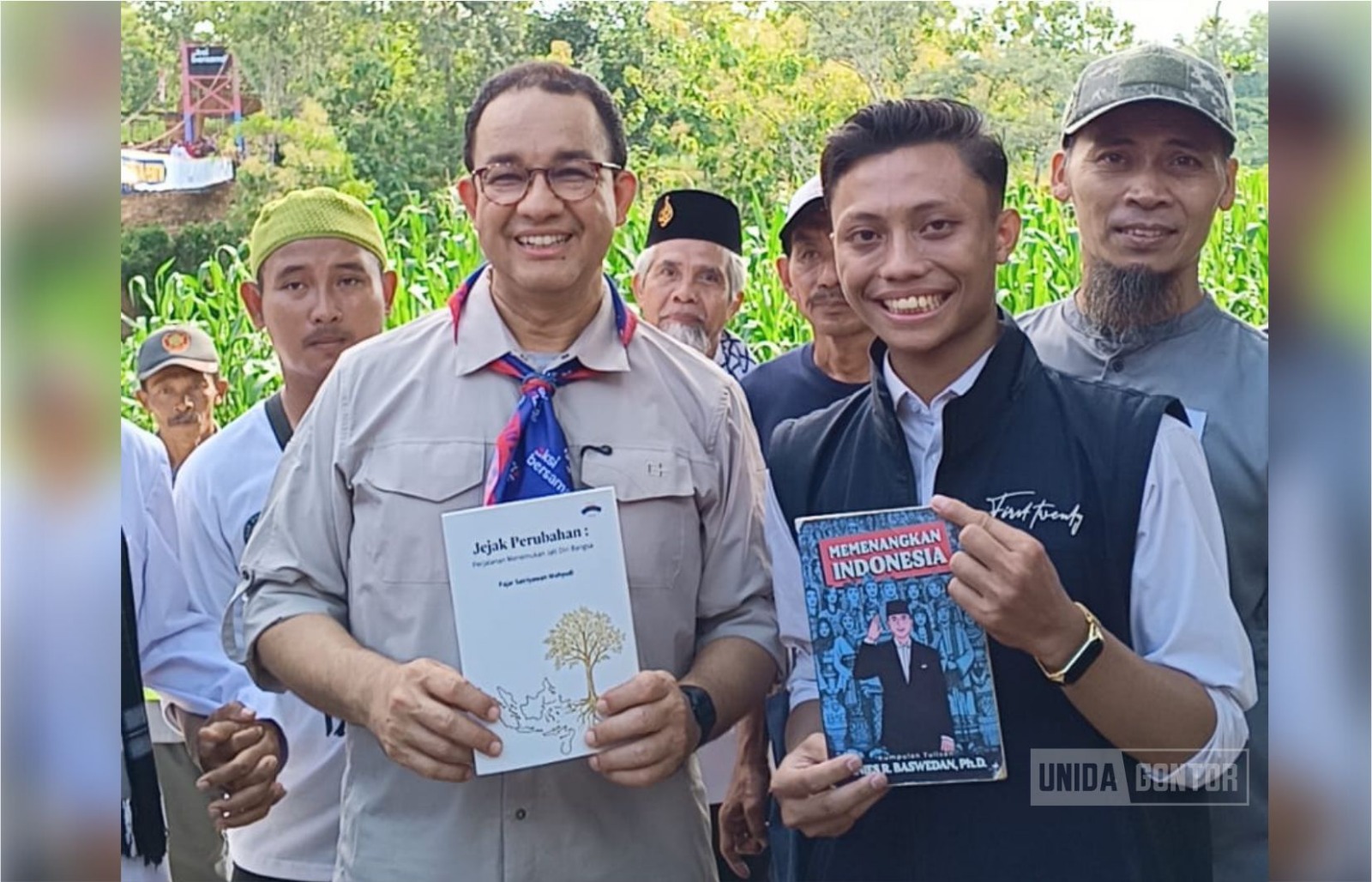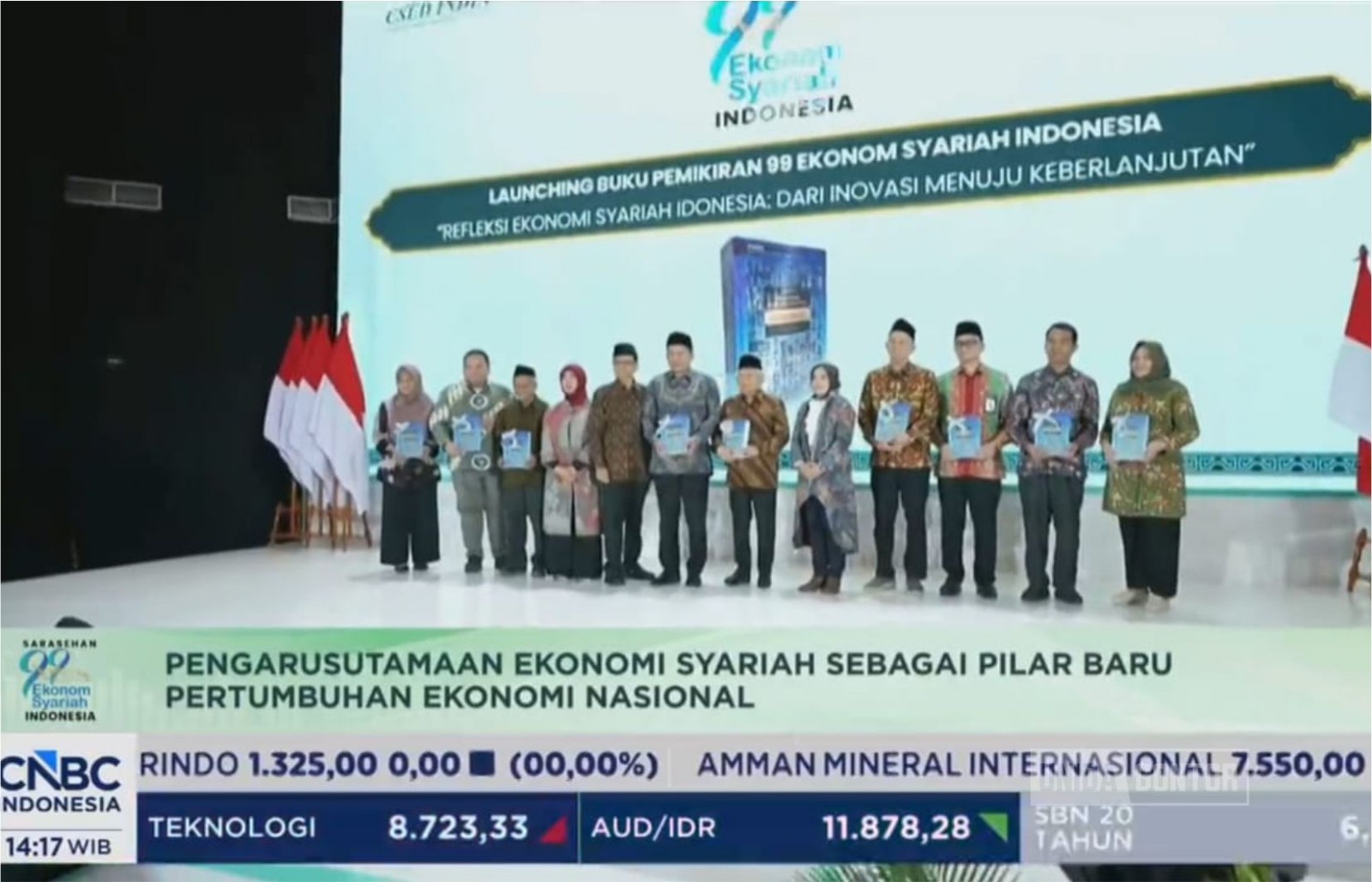“Tetaplah Berisik untuk Palestina” … Slogan tersebut seringkali melintasi beranda media sosial akhir-akhir ini. Bukan tanpa sebab, kalimat tersebut mengungkapkan betapa panjang perjuangan rakyat Palestina menghadapi kebrutalan zionis Israel sejak deklarasi Balfour (1917) diisukan. Kampanye pengusiran etnis Arab dari Palestina (1919) mengawali sejarah panjang settler colonialism Israel terhadap tanah Palestina. Tahun 1947 menjadi awal petaka bangsa Palestina, ketika PBB memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua negara, yang anehnya hingga saat ini rakyat Palestina sendiri belum mendapatkan kedaulatan mereka sepenuhnya. Peristiwa Nakhba (1948), Naksa (1967) dan pembantaian di Sabra-Satila melahirkan jiwa-jiwa ‘intifada’ yang justru diframing dalam narasi ‘teroris’ oleh Barat, sekutu kolonialisme Israel.
Peristiwa pengusiran paksa dan pendudukan wilayah penduduk Palestina oleh penjajah Israel kembali terjadi di tahun 2021 di pengungsian Syeikh Jarrah, 58 warga terusir dari tempat tinggal mereka termasuk diantaranya 17 anak (Hadi, 2021). Rentetan peristiwa pengusiran paksa, pendudukan dan pembantaian yang dilakukan zionis Israel terhadap Palestina melatarbelakangi serangan ‘Badai Aqsha’ oleh Hamas, yang kembali di narasikan zionis dan sekutunya sebagai ‘serangan teroris’. Namun saat ini, dunia tahu siapa ‘teroris’ sebenarnya, karena benang merah ‘kemanusiaan’ sesungguhnya nyata bagi manusia yang masih memiliki nilai kemanusiaan dalam dirinya. Palestina bukan sekedar perjuangan kedaulatan ataupun ideologi, namun Palestina adalah sebuah miniatur perjuangan kemanusiaan yang menjadi tolok ukur bagaimana gambaran manusia dan kemanusiaan global saat ini.
Manusia dan Kemanusiaan
Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai ‘zoon politicon’ atau makhluk politik, Rene Descartes menyebut manusia sebagai ‘res cogitan’ atau makhluk berfikir, Herbert Spencer memahami manusia sebagai ‘makhluk sosial’ yang berinteraksi dengan lainnya, Sigmund Freud lebih memaknai manusia dari sisi ‘ego’ yang berada atau dipengaruhi oleh keinginan (nafsu) atau prinsip moral, sementara dalam islam manusia disebutkan sebagai khalifah di bumi. Definisi tentang manusia beraneka ragam dalam berbagai sudut pandang, tapi penggambaran manusia oleh Thomas Hobes dalam dinamika politik (zoon politicon) menarik untuk dibahas, terutama dalam fenomena anarki sistem politik internasional saat ini, dimana Hobes lebih menekankan pada pendekatan berbasis konflik (Muhaimin, 2021).
Hobes menggambarkan manusia dengan istilah “homo homini lupus” atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Pernyataan Hobes jika dikaitkan dengan definisi manusia versi ilmu mantiq, sama-sama menyebut manusia yang memiliki kesamaan dengan binatang dalam sisi gelapnya. Dalam definisi ilmu Manthiq menyebutkan manusia sebagai “hayawan nathiq” atau binatang yang dapat berbicara, karena anugerah akal yang diberikan kepada manusia sebagai ‘pembeda’ antara manusia dengan binatang. Definisi tersebut didukung oleh definisi biologis, yang menyebut manusia dalam nomenklatur ‘homo sapiens’ atau primata mamalia yang memiliki otak kapasitas tinggi. Dalam konteks ini, manusia memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan sebagai manusia (sisi kemanusiaan) dan kecenderungan sebagai binatang (sisi kebinatangan). Ketika manusia cenderung pada sisi kemanusiaannya, maka hidupnya menjadi manfaat bagi sekitarnya karena akalnya yang selaras dengan nuraninya. Sebaliknya, saat manusia cenderung pada sisi kebinatangannya, maka hidupnya menjadi ancaman bagi sekitarnya, karena akalnya didominasi oleh nafsu dan mengabaikan nuraninya (Freud). Oleh sebab itu, kehidupan ini dapat berlangsung dengan baik dan kondusif, hanya saat manusia memiliki sisi kemanusiaannya dan bukan sebaliknya. Dalam konteks inilah lahir perspektif Realis dan Konstruktivis dalam dinamika politik dan hubungan internasional.
Kata ke-manusia-an dengan awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’ bermakna sebagai kata sifat, yaitu yang mensifati manusia atau dalam kata lain manusia-wi (bersifat manusia). Artinya, manusia tanpa sifat kemanusiaan akan kehilangan sifat asli nya sebagai manusia, dan cenderung kembali pada kategori primata atau binatang mamalia. Nilai kemanusiaan ini yang membedakan karakter dasar manusia dengan binatang, apabila nilai-nilai kemanusiaan hilang maka yang tertinggal adalah nilai-nilai kebinatangan. Sebaliknya ketika nilai kemanusiaan terjaga, maka akan menciptakan kehidupan dinamis, aman dan damai.
Palestina dan Krisis Kemanusiaan
Krisis kemanusiaan di Palestina menjadi indicator utama dalam menganalisis ‘sisi kemanusiaan’ masyarakat dunia saat ini, yang ditunjukkan dalam gerakan “GLOBAL MARCH TO GAZA”. Gerakan solidaritas kemanusiaan global, yang diikuti masyarakat sipil dari 90 negara pada 15 Juni 2025 lalu menjadi wujud bahwa sisi kemanusiaan masih ada dalam diri masyarakat internasional yang bersifat independent, netral dan universal tanpa melihat identitas ras, agama, maupun politik. Namun di sisi lain, nafsu kekuasaan dari sisi kebinatangan manusia membungkam perjuangan kemanusiaan global tersebut. Fenomena kegagalan Masyarakat sipil global dalam menyuarakan kemanusiaan, menjadi miniatur kondisi kemanusiaan di dunia saat ini. Kegagalan negara-negara dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza dan impunitas PBB dalam misi kemanusiaan di Gaza menjadi musibah besar bagi kemanusiaan di dunia. Jika nyawa ribuan anak-anak tak berdosa di Gaza tidak mampu membangkitkan sisi kemanusiaan seorang manusia, lantas dengan kebrutalan apalagi yang dapat membangun sisi kemanusiaan setiap manusia yang manusiawi?
Sejak serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 50.000 sipil Gaza menjadi korban pelanggaran prinsip proporsionalitas dan prinsip pembeda oleh Israel (MUI, 2025). Dr. Munir Al-Bursh, Dirjen Kementrian Kesehatan Jalur Gaza menyatakan, bahwa 65% penduduk Gaza tidak memiliki akses terhadap air bersih, 92% ibu dan anak-anak mengalami gizi buruk, dan 91% penduduk Gaza mengalami krisis pangan sejak Israel menerapkan blockade terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan yang ingin masuk ke Gaza 2 Maret 2025 hingga sekarang (Relief, 2025). Gencatan senjata hanya sebagai framing Israel pada masyarakat dunia, dimana pada hakekatnya mereka sengaja melakukan genosida terstruktur terhadap rakyat Palestina dengan menutup akses kemanusiaan dari berbagai arah. Krisis kemanusiaan di Palestina sudah berada pada level tertinggi, dimana puluhan ribu nyawa melayang tanpa mendapatkan akses bantuan kemanusiaan.
Jika nilai kemanusiaan tidak mendapatkan haknya di setiap sudut negara, maka situasi apa yang dapat menggambarkan gelapnya masa depan dunia tanpa sisi kemanusiaan? Manusia layak disebut manusia, ketika masih melekat sisi kemanusiaan dalam dirinya. Saat sisi kemanusiaan sebagai sifat yang mensifati manusia hilang, maka disitulah definisi manusiawi hilang dari dirinya dan hanya meninggalkan sifat hewaninya. Palestina menjadi alat ukur, apakah sisi kemanusiaan masih melekat dalam diri kita sebagai manusia atau sebaliknya. Maka, palestina, manusia dan kemanusiaan menjadi sebuah dialektika kehidupan global tentang fenomena manusia dalam sisi kemanusiaan yang mensifatinya. “You don’t need to be a moslem, you just need to be a human to stand with Palestine”, menjadi narasi yang tepat dalam melihat situasi krisis kemanusiaan akut di Palestina saat ini.
Redaksi: Ida Susilowati, M.A. (Dosen Hubungan Internasional Fakultas Humaniora UNIDA Gontor)